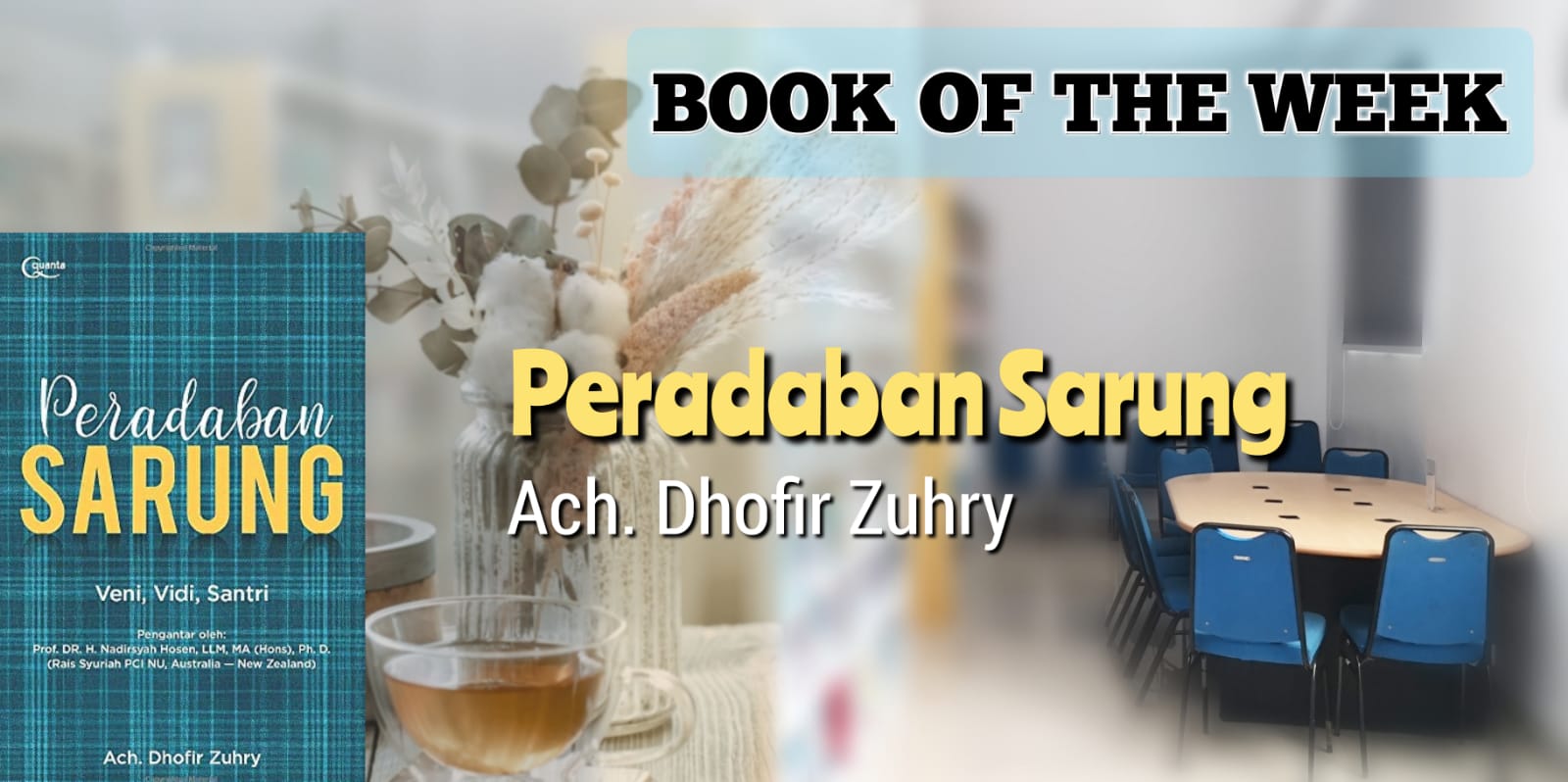Penulis : Ach. Dhofir Zuhry
Penerbit : Quanta
Tahun Terbit : 2018
Tebal Buku : xvi + 255
ISBN : 978-602-04-7705-3
Apa yang membedakan pesantren dengan pendidikan di luar pesantren? Apakah dari sistem pengajaran, kurikulum, metode, ataupun sarana dan prasarana? Memang, ada beberapa perbedaan di seputar hal-hal ini, namun tidak esensial. Apalagi sekarang ini telah terjadi perubahan-perubahan dan modifikasi dalam pendidikan pesantren dari banyak sisi.
Ada hal yang bersifat tetap dan tidak berubah yang menjadi akar pesantren yang membuatnya berbeda dan khas sebagai identitasnya sendiri. Drs. K.H. Ahmad Rifai Arief (2004: 252) menyebutkan kekhasan pesantren pada nilai-nilainya yang berlandaskan kepada jiwa keimanan, ketakwaan, keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah, dan kebebasan. Sistem pengajaran dan metode boleh berubah karena sesuai dengan perkembangan zaman, namun nilai-nilai pesantren tidak boleh berubah.
Buku Peradaban Sarung: Veni, Vidi, Santri yang ditulis oleh Ach. Dhofir Zuhry, mengangkat tema tentang nilai-nilai pesantren dan ragam unik kehidupan di dalamnya. Buku ini sarat dengan pandangan filosofis, etis, dan spiritual mengenai nilai-nilai pesantren. Buku ini juga bernada kritis terhadap nilai-nilai yang bertentangan dengan pesantren. Sebagai seorang santri yang kental dengan latar belakang pendidikan pesantren maupun pendidikan modern, buku yang ditulis Ach. Dhofir Zuhry ini menghadirkan cita rasa pesantren yang begitu kuat, bersama dengan sentuhan nalar kritis.
Buku ini relevan dalam rangka memahani nilai-nilai pesantren di tengah terjadinya banyak perubahan-perubahan di dunia pesantren yang rentan terhadap orientasi bisnis dan menyimpang dari khittahnya. Ketika pesantren mengalami “pengarusutamaan” (mainstreaming), seperti yang disebutkan oleh Prof. Azyumardi Azra, tentu menjadi penting untuk mempertahankan nilai-nilai pesantren. Kekhawatiran semacam ini sangat beralasan. Secara sederhana, hal itu muncul dalam suatu pertanyaan Kiai Rifai Arief ketika pesantren mengalami pembangunan. “Apakah santri masih bisa hidup sederhana?” Pertanyaan ini menyiratkan adanya tantangan besar yang dihadapi pesantren di tengah proses modernisasi dan perlombaan menjadi lembaga pendidikan yang bonafide.
Buku yang diberi kata pengantar Prof. Dr. Nadirsyah Hosen (Rais Syuriah PCI NU, Australia-New Zealand) ini merupakan kumpulan esai yang mengupas berbagai tradisi dan khazanah pesantren. Unsur-unsur utama pesantren, seperti santri, kiai, kitab kuning, barakah, ikhlas, hidup sederhana, dan sebagainya diulas dengan cukup gamblang dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Penulis menyebut bukunya ini sebagai, “tahapan-tahapan perjalanan mengenal ‘peradaban sarung’ yang saling bertali-temali satu sama lain” (hal. 98).
Santri dan Pesantren
Buku ini terbagi ke dalam empat bagian dengan sistematika yang tidak ketat, namun memiliki benang merah di setiap tulisan. Bagian pertama Veni, Vidi, Santri. Secara garis besar bagian ini membahas akar tradisi pesantren. Misalnya dalam “Filosofi Santri” istilah santri (serapan dari bahasa Sansekerta, shastri) memiliki makna khusus, yaitu sebagai gabungan dari huruf Arab sin, nun, ta’, ra’, dan ya’. Sin artinya salik ilal akhirah (menempuh jalan spiritual menuju akhirat). Nun maknanya na-ib ‘anil masyayikh (penerus para guru). Ta’ artinya tarik ‘anil ma’ashi (meninggalkan maksiat). Ra’ maknanya raghib ilal khayr (selalu menghasrati kebaikan). Ya’ artinya yarjus salamah (optimis terhadap keselamatan) (hal. 9).
Dalam “Veni, Vidi, Santri” diungkapkan mengapa menjadi santri merupakan pilihan. Santri datang (veni) ke pesantren bukan semata untuk meraih ilmu, tetapi untuk mengenal diri sendiri dan kemudian menaklukkan diri sendiri (vici). Setelah itu secara istikamah hidup menjalankan falsafah yang lima. Hal ini diperkuat dengan nilai kesederhanaan. “Pesantren mewajibkan para santri untuk terus menempa kedirian dan kepribadian, berlatih, bertapa, dan membentuk karakter. Kata kuncinya adalah hidup sederhana dan bersahaja. Orang-orang besar selalu dibentuk dengan kesederhanaan, bukan kemewahan materi” (hal. 10).
Betapa komprehensifnya nilai-nilai pendidikan pesantren, mencakup bagian yang sangat fundamental bagi kehidupan. Dalam “Panca Kesadaran Santri” dipaparkan lima kesadaran yang ditanamkan dan para santri wajib menjalankannya sebagai pusaka dan pedoman hidup, yaitu kesadaran beragama, berilmu, berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (hal. 15).
Dalam “Santri dan Modernitas”, ditunjukkan bagaimana santri tidak menolak modernitas, tapi mengarahkannya sesuai dengan filosofi wudhu dan salat. Sifatnya menyucikan, menundukkan, dan memasrahkan. “Pembangunan harus bersujud, industrialisasi harus membumi, pendidikan harus bersujud, kebudayaan tidak boleh menyelingkuhi tanah dan air, sistem politik pun harus paling sering dan rutin bersujud, agar manusia Indonesia tetap memiliki kewarasan dan kewajaran” (hal. 21).
Pendidikan pesantren memang bukan hanya menata aspek intelektual, tetapi juga terutama menata akhlak agar para santri menjadi generasi yang berakhlak mulia. Dalam “Ilmu Maju” diungkap bagaimana pendidikan pesantren menanamkan pendidikan yang mengubah pola pikir dan kebiasaan. “Pesantren mendidik kaum santri untuk hidup sederhana dan bersahaja, tidak menjadi peratap dan cengeng, makan dan hidup seadanya, kuat melek dan betah ngantuk, santri rela terhempas dari kenyamanan mimpi-mimpi demi ilmu dan barakah” (hal.33).
Kiai dan Keteladanan
Bagian kedua Pemimpin Orkestra, mengulas sosok kiai sebagai figur teladan. Di bahas pula kedudukan pesantren yang menghadapi tantangan modernisasi. “Sosok kiai ibarat seorang pemimpin orkestra. Ia tak menghadapkan wajahnya ke penonton, ketika kebanyakan orang di atas ‘panggung’ menghadap pada audiens dan mengharap sorak-sorai serta riuhnya aplaus sebelum dan sesudah beraksi. Tetapi seorang kiai tidak demikian. Baginya, bakti hidup, perhatian dan cinta-kasih tercurah semata untuk yang dipimpinnya, yakni santri dan umat yang kerap tersisih dan atau tertindih dibalik kejamnya rezim dan kekacauan sistemik” (hal. 64). Demikian pentingnya keteladanan kiai sebagai rujukan dan tempat kembali umat. “Kalau bukan kepada kiai, kepada siapa lagi eksistensi umat dapat dilekatkan dan dipertaruhkan” (hal. 64).
Sungguh tidak mudah peran seorang kiai. Ia menghadapi beragam tantangan berat maupun godaan syahwat duniawi. Dengan keteguhannya kiai tetap sabar dan istikamah. Dalam “Kiai Kampung” digambarkan bagaimana gelombang modernisasi dan globalisasi menggempur figur kiai dan pesantren. Namun mereka tetap teguh, meski dituding sebagai sumber keterbelakangan. “Justru para kiai tradisional dianggap biang kemunduran umat (Islam), sehingga penghormatan pada alim-ulama dianggap sebagai feodalisme. Dengan demikian, meminta berkah kepada kiai baik yang masih hidup dan lebih-lebih yang telah meninggal, dianggap syirik (menyekutukan Tuhan). Pesantren lalu dicibir sebagai kampungan, kumuh, jorok, tidak memiliki kurikulum yang jelas serta didaktik-metodik yang baik, tak lebih sekadar lembaga pendidikan yang sebenarnya hanya berisi pembodohan dengan iming-iming berkah dan tentu saja surga berikut bonus bidadari-bidadari molek. Pesantren kian terisolir, santri makin tersisih dari pergaulan hidup” (hal.78).
Namun daya tahan pesantren begitu kuat dan tak surut ke belakang. Perlahan tapi pasti, pesantren mengalami perubahan demi perubahan. Pesantren semakin mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Jumlah santri terus bertambah, meningkat secara signifikan ketika sekolah negeri maupun swasta gencar dengan pembangunan. Aneh, pesantren malah semakin kuat.
Dalam “Barakah” kita akan diajak untuk memahami mengapa santri percaya dengan berkah dalam menjalani kehidupan. “Barakah adalah nilai tambah dari secercah kebaikan yang pernah diperbuat” (hal. 86). Berakah berasal dari Allah yang dianugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya. “Santri, kiai (yang dulunya juga santri), dan para penganut ajaran Ahlus-Sunnah wal Jamaah sangat percaya pada barakah dan memang hidup mereka adalah demi meraih barakah itu” (hal. 86).
Pesantren harus berinovasi dan berkembang agar makin percaya diri. Karena kemajuan pesantren berarti kemajuan negeri ini, dan sebaliknya kemunduran pesantren berarti bobroknya negeri ini. Sementara pihak pemerintah harus memberikan dukungan terhadap tradisi keilmuan sebagaimana yang telah ditumbuhkan oleh pesantren . Dalam “Jualan Islam” hal ini dikemukakan dengan nada kritis. “Jika ditelaah secara jujur, salah satu penyebab kemunduran Islam dalam segala aspek kehidupan dan khususnya Indonesia adalah tidak beraninya pemerintah mengambil langkah nyata dengan membangun masyarakat ilmiah, yakni masyarakat yang cinta dan menjunjung tinggi ilmu dan kebudayaan dengan “mengakui’ pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal sebagai mercusuar ilmu di satu sisi, serta belum ‘pede’nya pesantren untuk berdiri sejajar dengan lembaga pendidikan modern ala barat” (hal. 109).
Dalam “Syahadat Kaum Sarungan” menjawab dikotomi antara ketuhanan dan kemanusiaan, seperti dalam kasus orang beragama yang keras, intoleran, dan tidak peka terhadap masalah-masalah sosial. Di sisi lain orang yang memperjuangkan kemanusiaan sembari mencibir agama sebagai biang konflik dan kekerasan. Maka syahadat kaum sarungan adalah syahadat ketuhanan kepada Allah Swt. dan syahadat kemanusiaan kepada Nabi Muhammad Saw. “Mengabaikan salah satunya adalah keliru, memilih salah satunya adalah jauh dari benar” (hal. 118). Jadi, harus keduanya, syahadat ketuhanan dan kemanusiaan. “Inilah syahadat kaum sarungan, para santri, dan penganut Ahlus-Sunnah wal Jamaah” (hal. 118).
Sejarah, Pendidikan, dan Tradisi Pesantren
Bagian Ketiga, Cita Rasa Pesantren mengungkapkan bagaimana identitas seorang santri yang selalu melekat erat, apa pun profesi yang ditekuninya. Santri tetap teguh dan setia, apa pun medan juang yang dihadapinya. Namun bagian ketiga ini nampaknya lebih menekankan pada aspek kesejarahan; awal mula dan sejarah perkembangan pesantren, metode pengajaran, dan tradisi pesantren. Termasuk lima elemen utama pesantren, yaitu masjid, pengajaran kitab klasik, kiai dan santri. Peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan, ilmu, dan akhlak.
Dalam “Peran” diungkapkan posisi pesantren yang terbuka terhadap tuntutan masyarakat, dan tidak menutup diri sebagai tafaqquh fid din saja. “Pesantren tidak hanya berkutat pada kurikulum yang berbasis keagamaan (religion-based curriculum) dan cenderung melangit, tetapi juga menerapkan kurikulum yang menyentuh persoalan kekinian masyarakat (society-based curriculum) yang cenderung membumi. Dengan demikian, pesantren tidak bisa lagi didakwa semata-mata sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga (seharusnya) menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespons carut-marutnya persoalan masyarakat di sekitarnya” (hal.177).
Jenis-jenis pesantren seperti pesantren salaf, modern, luhur (pesantren khusus mahasiswa) dengan cirinya masing-masing juga dikemukakan pada bagian ini, meski tidak untuk dinilai kelebihan maupun kekurangannya. Bagaimanapun, hal itu adalah perbedaan yang tidak dapat dihindari.
Pesantren, Keislaman, dan Keindonesiaan
Bagian keempat, Menjadi Santri, Menjadi Indonesia. Bagian ini membahas masalah identitas keindonesiaan kita, ketika westernisasi membanggakan identitas budaya Barat, sementara Arabisme membanggakan budaya Arab (karena dianggap lebih asli dan Islami), lantas meniru secara fanatik, mencibir identitas keindonesiaan. Padahal kita hidup, tumbuh, dan berkembang di tanah Indonesia. “Di sinilah mengapa kita para santri lebih memilih menjadi Indonesia daripada menjadi yang lain” (hal.204).
Sikap intoleran dan fanatisme golongan mendapat ulasan dalam “Agama Permen Karet.” Sikap semacam ini sering ditudingkan ke pesantren ketika isu-isu radikalisme menguat di publik. Hal itu jelas keliru. Pesantren justru memiliki peranan dalam menumbuhkan budaya toleransi. “Salah satu keberhasilan pesantren dalam mendidik para santri adalah mengajarkan toleransi dan menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengalah demi perdamaian dan harmoni umat manusia, serta lebih mengedepankan pekerti yang luhur dalam keseharian daripada bersitegang dengan siapa pun yang berbeda. Membiarkan orang lain riang-gembira dengan warnanya masing-masing adalah ajaran para kiai dalam rangka menomorsatukan Indonesia daripada perbedaan mazhab, pandangan politik, dan ekspresi budaya” (hal.206).
Lalu, sejauh manakah pesantren melakukan perubahan pada masyarakat. Bisakah sorban dan sarung mengubah kultur dan bahkan peradaban umat manusia, khususnya Nusantara? Jika tiga hal berikut ini bisa diubah, maka jawabannya bisa. Pertama, spiritualitas dan religiositas; kedua, moralitas generasi muda; ketiga, intelektualitas. Berdasarkan nilai-nilai yang ditanamkan pesantren maupun fakta sejarah peran pesantren, kita boleh optimis untuk hal ini.
“Para santri dididik dengan membiasakan mengenakan sasarung. Sarung adalah kata lain dari syar’un (syariat, aturan agama). Itu artinya pesantren memegang teguh syariat Islam tanpa berteriak-teriak di pinggir jalan dan demo berjilid-jilid. Santri juga mengenakan baju koko atau baju taqwa, bukan sembarang baju. Tak kalah penting, kiai mencontohkan santri agar biasa menggunakan bakiak atau terompah, alas kaki tradisional dari kayu. Bakiak berasal dari kata baqyaq yakni baqa’ (tetap) dan yaqin (mantap). Artinya santri senantiasa tetap konsisten dengan tradisi dan mantap menjalankan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tak ketinggalan, santri juga biasa menggunakan kopiah, yang berasal dari kata Arab khufyah (samar, sembunyi). Ini menandakan bahwa santri senantiasa menyamarkan kecerdasan dan kepandaiannya, tidak sok dan ugal-ugalan. Santri selalu menyembunyikan kebaikan dan kesalehannya, anti pencitraan dan ikhlas dalam berpikir, bertutur dan bertindak. Jika demikian, masihkah kita anti sarung, kopiah, dan bakiak?” (hal.221).
Ada sebagian anggapan bahwa santri adalah pemalas. Padahal dalam pendidikan pesantren segala aktivitasnya memiliki aturan. Ada kedisiplinan dalam melaksanakan kebiasaan sehari-hari. Justru pada sisi inilah pembentukan karakter terjadi. Dalam “Bi(a)sa”, masalah kedisiplinan hidup di pesantren mendapatkan tekanan. “Satu hal yang paling menonjol dari kultur pesantren adalah kedisiplinan, budaya antri dan pembiasaan. Belajar, mengaji, mandi, memasak, makan, kerja bakti, tidur, bangun malam, semua dikerjakan dengan disiplin dan tepat waktu. Pembiasan semacam inilah yang membentuk mental dan karakter Santri” (hal.235).
Tulisan berakhir dengan “Keseharian Santri, Indonesia Kini dan Nanti”, yang menekankan peran santri di masyarakat. Bagaimana ia mendedikasikan ilmunya bagi kepentingan umat. Tantangan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks dan membutuhkan kehadiran santri sebagai kaum terdidik yang menimba ilmu, ditempa disiplin akhlak. Bijak dan toleran di tengah keragaman.
“Tantangan dalam bermasyarakat, bagaimana membangun sinergi antara agama dan negara acap kali membenturkan kaum sarungan untuk kreatif dan inovatif serta fleksibel dalam berpikir dan bertindak. Islam itu satu, mazhabnya banyak. Indonesia itu satu, perbedaan pendapat dan benturan kepentingan penduduknya keramat banyak dan kompleks” (hal.248).
Kiai, santri, dan pesantren terus melayani umat sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip dan nilai-nilai tidak pernah berubah. Buku Peradaban Sarung telah memberikan pemahaman pada kita betapa kayanya nilai-nilai, khazanah, dan kehidupan pesantren yang tidak akan ditemukan dalam pendidikan di luar pesantren. Ini menjadi harapan ke depan bahwa pesantren memiliki alasan kuat untuk terus bertahan, bahkan bersaing dengan lembaga pendidikan lain tanpa kehilangan identitasnya. Pesantren akan terus memberikan manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, sebagaimana peranan yang telah ditunjukkan sejak awal masa dakwah Islam di Nusantara, perjuangan di masa kolonial, kebangkitan di masa kemerdekaan, hingga sekarang maupun di masa mendatang.